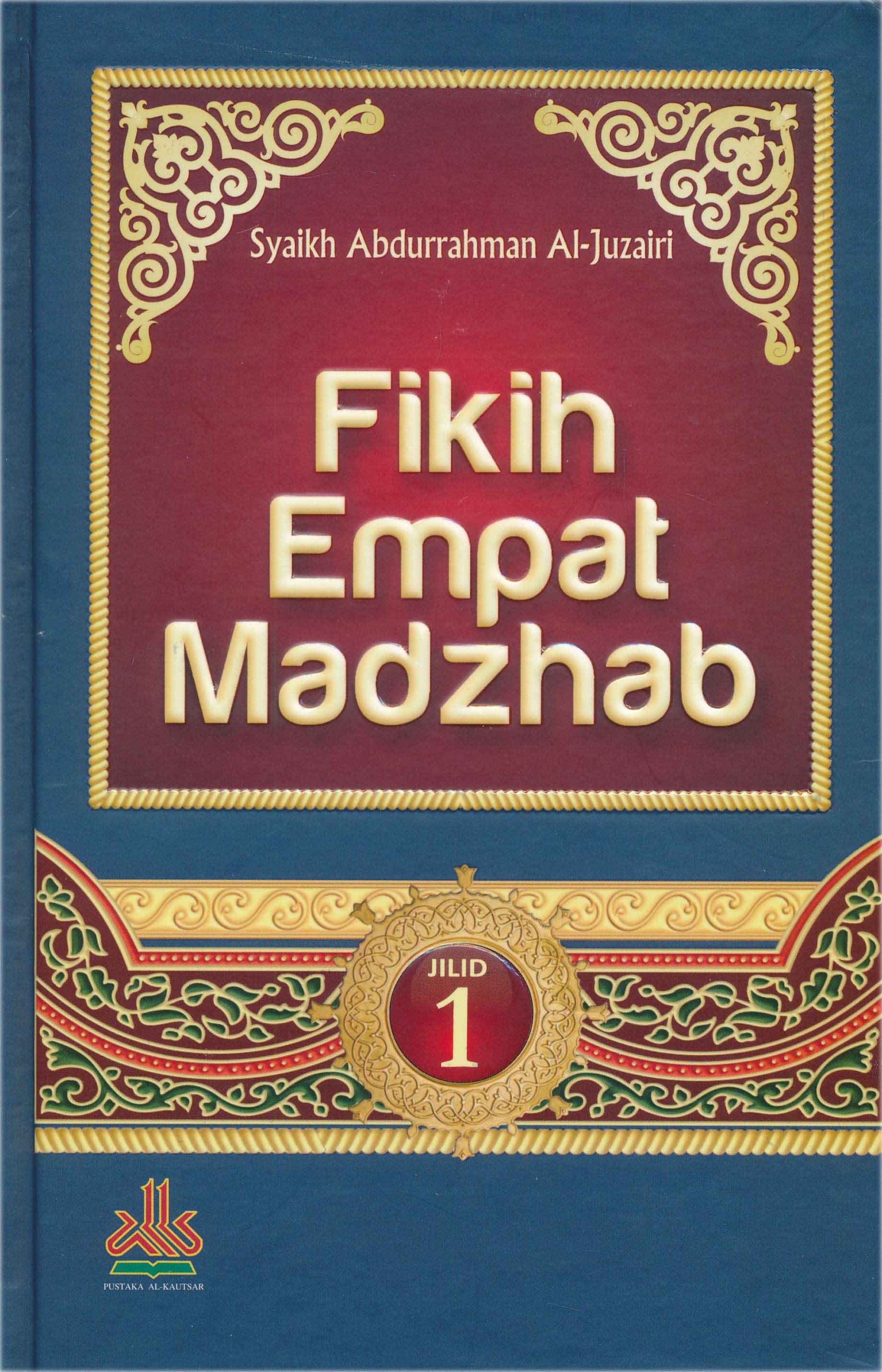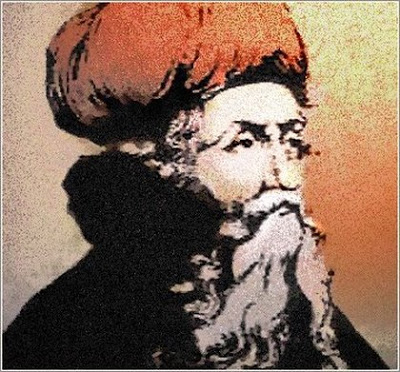ADA beberapa pembahasan terkait tema wudhu ini, mulai dari definisi, hukumnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, dan hal-hal yang membatalkannya, hingga istinja’ atau cara bersuci alternatif dari faktor-faktor yang membatalkan wudhu.
Definisi Wudhu
Secara etimologi, wudhu berarti kebaikan dan kebersihan. Adapun maknanya dalam istilah fikih adalah menggunakan air pada anggota anggota tubuh tertentu, seperti wajah, tangan dan seterusnya, dengan cara
yang tertentu pula.
Hukum wudhu
Yang dimaksud hukum di sini adalah akibat (amalan) yang muncul setelah terpenuhinya wudhu. Misalnya hilangnya hadats kecil, lalu dibolehkannya menunaikan shalat fardhu mauPun shalat sunnah, sujud tilawah, thawaf mengelilingi Al-Bait (Ka’bah) baik yang bersifat wajib maurupun sunnah.33
Rasulullah Saw bersabda,
“Thawaf mengelilingi Ka’bah itu seperti shalat. Hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya. Maka, barangsiapa yang berbicara dalam thautafnya,
hendaknya ia tidak berbicara kecuali yang baik. ” (HR. At-Tirmidzi dengan
sanad hasary dan Al-Hakim)
33 Madzhab Hanafi mengatakan; Barangsiapa yang thawaf di Al-Balf (Ka’bah) tanpa wudhu, maka thawafnya sah. Namun, ia haram melakukannya. Sebab, suci dari hadats itu waiib untuk thawaf. Dan barangsiapa yang meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Tetapi, ia bukan syarat sahnya thawaf.
Kaitannya dengan amalan thawaf maupun shalat, wudhu menjadi fardhu atau wajib. Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu melakukan amalan tersebut. Begitu pula halnya dengan menyentuh mushaf, maka ia harus memiliki wudhu.
Sama saja apakah ia bermaksud menyentuh keseluruhan mushaf atau hanya sebagian saja, atau bahkan hanya satu ayat saja. Namun demikian, ada beberapa pengecualian dalam berbagai madzhab fikih.
Madzhab Maliki mengatakan; Boleh menyentuh mushaf, baik sebagiannya atau seluruhnya, dengan tanpa wudhu, tetapi dengan beberapa syarat.
Syarat pertama; Hendaknya mushaf tersebut ditulis dengan selain bahasa Arab. Adapun jika tertulis dengan bahasa Arab, maka haram menyentuhnya dalam kondisi apa pun. Kedua; Tertulis di atas uang dirham atau dinar atau yang semacamnya, di mana orang-orang mensunakannya untuk transaksi jual beli. Ini karena menghindari kesulitan. Ketiga; Dia mengambil mushaf semuanya atau sebagiannya untuk semacam jimat.
Tetapi sebagian dari mereka mengatakan; kalau membawa sebagiannya
boleh, adapun jika membawa semuanya tidak boleh. Namun bolehnya
ini juga dengan dua syarat, yaitu: yang membawa orang muslim, dan
mushafnya mesti dalam keadaan tertutup yang menghalangi agar tidak
terkena kotoran. Keempat; Yang membawanya adalah seorang pengajar
atau orang yang sedang belajar, sekalipun ia perempuan yang lagi haidh.
Selain keempat syarat di atas, tidak boleh memegang mushaf tanpa
wudhu, apa pun kondisinya, baik dengan sampul maupun memegang
langsung. Bahkan, jika mushaf itu terletak di atas kotak atau bantal atau
kursi, dia tidak boleh membawanya. Sedangkan jika mushafnya terdapat
pada suatu barang, maka dia boleh membawa barang tersebut. Namun
jika hanya membawa mushafnya saja, tidak boleh. Adapun membaca Al-
Qur’an tanpa memegang mushaf, hukumnya boleh bagi yang tidak punya
wudhu. Tetapi yang utama adalah dengan berwudhu.
Madzhab Hambali mengatakan; Disyaratkan bagi orang yang hendak
membawa atau memegang mushaf tanpa wudhu, hendaknya mushaf
tersebut dihalangi sesuatu yang terpisah. Sekiranya itu adalah sampul
yang menempel pada mushaf, seperti jika berada di dalam kantong atau
terbungkus kain atau daun atau berada di dalam kotak, dan sebagainya,
maka boleh memegangnya atau membawanya. Begitu pula, boleh
menjadikan mushaf sebagai iimat dengan syarat ia harus tertutup rapat
dengan penutup yang suci. Selanjutnya, wudhu adalah syarat bolehnya
membawa mushaf, baik untuk mukallaf maupun yang belum mukallaf.
Tetapi anak kecil yang belum baligh tidak wajib wudhu. Orang tuanyalah
yang wajib menyuruh anaknya untuk wudhu jika si anak hendak membawa
mushaf.
Madzhab Hanafi mengatakan; Ada sejumlah syarat untuk bolehnya
menyentuh mushhaf semuanya atau sebagiannya atau menuliskannya, yaitu:
Pertama;Dalam keadan darurat, seperti kalau takut mushafnya tenggelam
atau terbakar. Di sini, boleh memegang mushaf untuk menyelamatkannya.
Kedua;Hendaknya mushaf tertutupi dengan sesuatu yang terpisah, seperti
berada di dalam kantong plastik, kantong kulit, atau daun atau terbungkus
kain, atau semacarmya. Dalam kondisi demikian, boleh memegangnya
dan membawanya. Adapun kalo pembungkusnya atau pelapisnya itu
bersambung langsung dengan mushafnya, di mana ia berada satu paket
dalam penjualannya, maka ia tidak boleh dipegang, meskipun sampulnya
terpisah. Demikian menurut fatwa yang muktabar dalam madzhab
ini. Ketiga; yang memegangnya adalah anak yang belum baligh untuk
mempelajarinya, demi menghindari kesulitan. Adapun orang yang sudah
baligh, atau perempuan yang sedang haidh, entah itu pengajar ataupun
pelajar, maka tidak boleh bagi keduanya menyentuh mushaf. Keempat;
Mesti seorang muslim. Orang non-muslim tidak boleh memegang mushaf
meskipun dipersilakan oleh seorang muslim. Muhammad bin Al-Hasan
berkata;’Orang non-muslim boleh memegang mushaf apabila dia mandi
dulu.’ Adapun orang non-muslim yang menyimpan mushaf, hukumnya
boleh. jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka orang yang tidak suci
dan tidak punya wudhu tidak boleir memegang mushaf dengan tangannya
maupun anggota tubuhnya yang lain. Adapun membaca Al-Qur’an tanpa
mushaf, maka ia boleh bagi orang yang tidak Punya wudhu, selain orang
yang junub dan perempuan yang haidh. Tetapi tetap disukai membaca
Al-Qur’an dengan wudhu.
Demikian. Adapun untuk kitab tafsir, maka hukumnya makruh memegangnya. Sedangkan kitab-kitab fikih, hadits, dan lain-lairy maka
boleh memegangnya tanpa wudhu, di mana ia termasuk rukhshah
(keringanan).
Madzhab Asy-Syafi’i mengatakan; Boleh memegang atau membawa sebagian mushaf maupun semuanya dengan beberapa syarat. Pertama;
Membawanya sebagai jimat. Kedua; Tertulis pada uang dirham atau
pound Mesir. Ketiga; Sebagian Al-Qur’annya tertulis pada kitab-kitab ilmu, sebagai dalil. Tidak ada bedanya baik yang tertulis itu sedikit atau banyak. Adapun kitab-kitab tafsir, maka boleh memegangnya tanpa wudhu dengan syarat tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Sekiranya Al-Qur’annya yang lebih banyak, maka tidak boleh memegangnya. Keempat; Ayat-ayat Al-Qurannya tertulis pada pakaian, seperti yang tersulam pada kiswah Ka’bah dan semacamnya. Kelima; Memegang karena untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, orangtua atau wali boleh membiarkan anaknya memegang dan membawa Al-Qur’an untuk belajar. Sekalipun si anak hafal Al-Qur’an di luar kepala.
Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram hukumnya memegang Al-Qur’an, meskipun hanya satu ayat, meskipun terhalang dengan sesuatu yang terpisah, dan meskipun ia terletak di suatu tempat, seperti tempat yang dipakai untuk meletakkan mushaf-mushaf. Juga tidak boleh menyentuhnya sekalipun mushaf tersebut terletak di atas kursi kecil, seperti kursi yang dibuat untuk meletakkan mushaf Al-Qur’an.
Pada saat membaca AI-Qur’an pun tidak boleh memegang tempat atau kursi yang diletakkan mushaf di atasnya. Adapun jika mushafnya diletakkan di kotak yang besar atau kantong yang besar, maka tidak haram menyentuh kotak atau kantongnya, kecuali bagian yang sejajar dengan mushaf. Dan sekiranya kalit sampul mushaf terlepas, di mana tidak ada lembaran yang tersisa, maka tetap haram memegangnya kecuali jika sampul kulit itu digunakan untuk menyampuli kitab yang lain selain Al-Qur’an.
Selanjutnya jika mushaf terletak pada peralatan rumah tangga, seperti rak, pakaian, dan sebagainya, maka tidak boleh membawa perkakas ini tanpa wudhu, kecuali jika maksudnya adalah hanya membawa perkakasnya saja, bukan membawa mushaf. Namun jika niatnya adalah membawa keduanya atau hanya membawa mushafnya saja, hukumnya haram tanpa wudhu.
Syarat-syarat Wudhu
Syarat-syarat wudhu dibagi menjadi tiga: pertama, syarat wajib. Kedua,
syarat sah. Ketiga, syarat wajib dan sah secara bersamaan.
Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah syarat yang mengharuskan seseorang untuk mengerjakan wudhu. Jika salah satu atau sebagian dari syarat atau kondisi tersebut tidak terwujud, maka ia tidak berkewajiban wudhu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sah adalah syarat di mana wudhu menjadi tidak sah tanpa terpenuhinya syarat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan syarat wajib dan syarat sah secara bersaman adalah syarat yang apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka melakukan wudhu menjadi tidak wajib dan apabila tetap melakukan wudhu maka wudhunya tidak sah.
Contoh untuk syarat wajib wudhu adalah baligh. Orang yang belum baligh tidak berkewajiban wudhu, baik laki-laki maupun Perempuan. Tetapi, wudhu orang yang belum baligh tetap sah sepanjang terpenuhi syarat-syarat sahnya. Kalau saja seseorang berwudhu satu jam sebelum mencapai baligh, hal itu tidak menjadikan wudhunya batal. Dia tetap boleh melanjutkan wudhunya dan melaksanakan shalat dengan wudhu tersebut. Meskipun hal ini sangat jarang terjadi, namun bagi para musafir atau penduduk di padang sahara, tentu sangat bermanfaat, mengingat keterbatasan air yang mereka miliki.
Contoh lain misalnya, ketika telah masuk waktu shalat. Saat waktu shalat telah masuk, maka wajib bagi seorang mukallaf untuk melakukan shalat di rentang waktu yang disediakan untuk shalat tersebut. Ketika shalat itu sendiri tidak boleh dilaksanakan tanpa wudhu lebih dulu, maka wudhu di sini menjadi wajib. Mengingat bahwa shalat menjadi wajib terhitung sejak waktunya telah masuk hingga waktunya habis, maka demikian pula halnya denganwudhu, yang mana shalat tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpanya. Artinya, bahwa kewajiban yang ada merupakan kewajiban yang longgar, yaitu terhitung sejak memasuki waktu shalat hingga habis waktunya. Dalam istilah fikih dikenal waktu “muwassa” atau waktu yang longgar. Di mana seorang mukallaf diperbolehkan melaksanakan shalat di awal, di tengah, atau bahkan di akhir waktunya. Manakala waktu shalat hanya tersisa sebatas untuk berwudhu dan shalat saja, maka dalam keadaan semacam ini kadar wajibnya berubah menjadi wajib mudhayyaq (wajib yang sempit), yaitu ia hendaknya melaksanakan wudhu dan shalat sesegera mungkin. Kalau sampai memperlambat wudhu dan shalat atau terlambat dari waktu yang tersedia, maka ia berdosa. Sama seperti wudhu yang wajib bagi mereka yang hendak melaksanakan shalat fardhu, maka wajib pula berwudhu bagi yang hendak melaksanakan shalat sunnah. Kapan seseorang berniat melaksanakan shalat sunnah, maka sesegera itu pula ia wajib berwudhu. Jika tidak, ia tidak dibolehkan melakukan shalat tanpa berwudhu terlebih dulu.
Jika Anda tahu bahwa masuknya waktu merupakan syarat wajibnya wudhu saja, maka Anda juga mengerti bahwa wudhu tetap sah jika dilaksanakan sebelum masuknya waktu shalat. Sebab, masuknya waktu shalat bukan merupakan syarat sahnya wudhu, kecuali jika orang yang dimaksud sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan.34 Misalnya, orang yang mengidap penyakit beser (sebentar-bentar kencing). Orang seperti ini wudhunya tidak sahkecuali dilakukan setelah memasuki waktu shalat. Jadi orang seperti ini berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah masuk. Selain itu adalah orang yang belum berwudhu sebelum memasuki waktu shalat. Apabila seseorang sudah berwudhu untuk shalat zhuhur, lalu ia tidak batal selama sehari penuh maka ia tidak berkewajiban wudhu ketika waktu shalat ashar tiba, misalnya.
Anda sudah mengerti bahwa wudhu yang dilaksanakan sebelum masuk waktu shalat adalah sah. )adi ia tidak berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah tiba apabila ia masih memiliki wudhu sebelumnya.
Sebaliknya, apabila ia tidak memiliki wudhu sebelum masuk waktu shalat,
maka ia berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah masuk. Di samping
34 Madzhab Maliki mengatakan; Wudhunya orang yang ada udzur (seperti sakit beser) adalah sah, sebelum masuk waktu dan setelahnya.
Madzhab Hanafi mengatakan; Wudhunya orang yang ada udzur adalah sah, sebelum masuk waktu. Jika misalnya dia wudhu sebelum zuhur, kemudian masuk waktu zuhur, wudhunya tidak batal. Dia boleh shalat dengan wudhunya itu pada waktu zuhur. Apabila telah lewat waktu zuhur, wudhunya tidak berlaku lagi. Dia tidak sah shalat ashar kecuali dengan wudhu baru. Engkau akan tahu sebab kenapa wudhunya tidak berlaku setelah
lewat waktunya, nanti pada pembahasannya. Dengan itu engkau tahu, bahwa apa yang disebutkan di atas adalah madzhab Asy-Syafi’i dan Hambali.
itu, ia haruslah orang yang sanggup untuk melaksanakan wudhu. Orang
yang tidak sanggup/ misalnya tidak dapat menggunakan air karena suatu
halangan atau penyakit, ia tidak berkewajiban wudhu.
Adapun syarat sahnya wudhu saja, di antaranya adalah air yang digunakan harus suci mensucikan. Pembahasan mengenai air suci mensucikan sudah kami paparkan sebelumnya, dan bagi orang yang berwudhu cukup meyakini bahwa air yang digunakan untuk berwudhu adalah benar-benar air suci mensucikan. Orang yang berwudhu harus sudah mumayyiz. Dengan demikian, maka anak kecil yang belum mumayyiz wudhunya tidak sah. Termasuk pula syarat sahnya wudhu hendaknya tidak ada penghalang yang mencegah air sampai pada anggota badan yang dimaksud untuk dibasuh. Kalau sampai ada sesuatu yang menempel pada tangan atau wajah atau kaki atau kepala di mana sesuatu tersebut dapat menghalangi air mencapai kulit, wudhunya tidak sah. Hendaknya juga orang yang berwudhu tidak mengalami hal-hal yang dapat membatalkan wudhu selama berwudhu. Kalau misalnya seseorang sedang membasuh muka atau tangannya tiba-tiba ia berhadats, maka ia harus memulai wudhu lagi dari awal, kecuali mereka yang masuk kategori orang-orang yang memiliki halangan tetap, seperti orang yang mengidap penyakit beser. Kalau selama melakukan wudhu tiba-tiba terasa tetesan-tetesan air kencingnya akibat penyakit, ia tidak perlu mengulangi wudhunya.
Adapun syarat-syarat wajib dan sah secara bersamaan, di antaranya adalah berakal. Orang gila tidak wajib wudhu,35 begitu pula orang yang kesurupan, orang idiot,36 dan orang yang pingsan. Apabila salah satu dari mereka berwudhu, itu tidak sah. Andaikata ada orang terkena epilepsi berwudhu sesaat kemudian ia sembuh dari penyakitnya, maka tidak sah shalatnya dengan wudhu tersebut. Demikian pula orang dengan orang
35. Madzhab Hanafi mengatakan; Gila, kesurupan, dan yang semacamnya dari sejumlah sebab yang membatalkan wudhu yang telah disebutkan di atas, maka ia meniadakan
keshahihan wudhu. Karena inilah, ia termasuk dari syarat-syarat sahnya wudhu. Dan,
engkau telah mengetahui, bahwa ia termasuk syarat-syarat wajibnya wudhu menurut
mereka. Dengan demikian ia termasuk syarat wajib dan sah secara bersamaan.
36. Madzhab Hanafi mengatakan; Orang idiot yaitu orang yang bicaranya tidak nyambung
dan tidak bisa merencanakan sesuafu, meskipun penampilannya tenang dan tidak suka
memaki-maki orang lain. Dia juga masih tahu jalan dan tidak suka memukul. Yang seperti
ini, ibadahnya sah, seperti anak kecil. Tetapi, tidak wajib baginya. Sebab, tidak idiot itu
termasuk syarat wajib saja. Bukan termasuk syarat sah.
gila. Adapun orang yang terserang epilepsi atau orang yang tidak sadarkan
diri, tentu tidak terbayang bagaimana mereka dapat mengerjakan wudhu.
Akan tetapi menyebut contoh-contoh seperti ini adalah bertujuan untuk
menjelaskan bahwa Allah telah mengangkat atau menggugurkan beban
kewajiban apa pun atas diri mereka. Ini juga untuk menunjukkan bahwa
tindakan hukum dalam ranah ibadah adalah sebagaimana tindakan tindakan
lain dalam ranah muamalah. Bahwa dalam dua ranah ini harus
memenuhi unsur sehat akal pikiran.
Di antara syarat sah dan wajib secara bersamaan adalah terbebasnya
wanita dari haidh dan nifas. Tidak diwajibkan bagi wanita yang haidh
dan nifas untuk berwudhu, dan tidak sah pula wudhunya. Kalau saja ia
berwudhu sementara masih dalam keadaan haidh lalu sesaat kemudian
selesai haidhnya, maka wudhunya sama sekali tidak diperhitungkan karena
tidak sah. Benar bahwa wanita haidh dianjurkan untuk berwudhu di tiap
waktu shalat, dan duduk di tempat shalatnya, sebagaimana akan kami
jelaskan pada bab haidh. Tetapi, perlu diketahui bahwa wudhu tersebut
hanyalah wudhu yang bersifat permukaan saja dan tidak mengandung
substansi wudhu sebagai bagian dari ibadah. Tujuannya tidak lain untuk
menjaganya tidak sampai melupakan shalat ketika ia berada pada masa
meninggalkan shalat tersebut.
Termasuk pula syarat wajib dan sah adalah tidak dalam keadaan
tidur dan tidak dalam keadaan lupa. Orang tidur tidak terkena beban
hukum apa pun selama masa tidurnya sebagai rahmat baginya, demikian
pula orang yang lupa. Jika saja diwajibkan dan benar terlaksana wudhu
pada mereka, maka wudhu tersebut terlaksana secara tidak sah. Mungkin
ada sebagian orang mengira bahwa yang dimaksud orang tidur adalah
mereka yang terkapar di tempat tidurnya, tentu saja tidak terbayangkan
bagaimana bisa mereka melakukan wudhu. Yang dimaksud tidur di sini
adalah orang yang masihbisa berdiri dan melakukan gerakary bahkanbisa
berjalan keluar dari rumahnya padahal dia dalam keadaan tidur. Orang
dalam keadaan seperti ini bagaimana tidak sah wudhunya, karena dia tidur
dan tidak menyadari apa pun. Saya sendiri pernah melihat tetangga saya
dalam kondisi seperti ini.
Termasuk syarat wajib dan sah adalah Islam.37 Islam merupakan syarat
37 Madzhab Malif.i -*gutuLun; Beragama Islam adalah syarat sahnya saja. Itulah, orang-orang kafir menurut mereka itu tetap wajib menjalankan cabang-cabang syariat. Mereka wajib beribadah, dan berdosa jika meninggalkan. Namun, itu tidak sah kecuali setelah
mereka masuk Islam. Hanya saja, ketika mereka masih kafir, ibadahnya tidak sah. Karena semua ibadah harus disertai dengan niat, menurut mereka (madzhab Maliki). Dan, engkau sebentar lagi akan mengetahui bahwa di antara syarat-syarat sahnya niat adalah beragama Islam.
Madzhab Hanafi mengatakan; Sesungguhnya agama Islam adalah termasuk syarat wajib saja. Tidak termasuk syarat wajib dan sahnya suatu ibadah secara bersamaan. Kebalikan dengan Malikiyah menurut mereka, orang kafir tidak dituntut dengan cabang-cabang syariat. Mereka hanya menganggap tidak termasuk syarat sahnya ibadah. Karena, menurut mereka, wudhu itu tidak harus dengan niat. Sebab, niat tidak termasuk rangkaian
fardhunya wudhu. Berbeda dengan tayamum. Sesungguhnya tayamum itu tidak sah dari seorangkafir, karena ia harus didasari denganniat. Sebab, niat itu fardhu dalam tayamum.
wajib, dalam arti bahwa non-muslim tidak dituntut untuk berwudhu, yakni orang kafir. Tetapi, dalam keadaan kafirnya, mereka tetap masuk kategori orang yang terkena khitab untuk shalat dan segala sesuatu yang menunjangnya. Dalam hal ini, mereka dihukum karena tidak mengerjakan
wudhu, akan tetapi di sisi lain mereka juga tidak sah mengerjakan wudhu,
karena kekafirannya. Termasuk syarat wajib dan sah secara bersamaan adalah sampainya dakwah Nabi Muhammad Saw.38 Hendaknya orang tersebut mengetahui bahwa Allah telah mengirim utusan untuk semua umat manusia yang menyeru kepada umat manusia untuk bertauhid kepada Alah. Mensifati Allah dengan segala sifat ke-Mahasempurnaan. Menyeru umat manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Siapa yang kepadanya
tidak sampai dakwah Rasulullah 6 ini, maka baginya tidak diwajibkan
melakukan apa pun dari perintah dan seruan-seruan tersebut. Baginya
pula tidak diwajibkan berwudhu. Demikian juga tidak sah wudhu orang
yang belum sampai kepadanya dakwah Rasulullah Saw. Kalau orang
tersebut berwudhu, maka wudhunya tidak sah. Dan sekiranya sesaat
setelah itu ia menerima dakwah Rasulullah, wudhu yang telah ia kerjakan
sesaat sebelumnya tetap tidak sah. Selain ini beberapa madzhab ada yang
menambahkan syarat-syarat lain sebagaimana tertulis di catatan berikut.
38 Madzhab Hanafi mengatakan; Sampainya dakwah bukanlah syarat sahnya wudhu. Sekiranya ada orang yang wudhu sebelum dakwah sampai kepadanya, kemudian dakwah itu sampai kepadanya di mana dia dalam keadaan sudah berwudhu, maka wudhunya sah.
Tetapi sampainya dakwah tidak dianggap sebagai syarat waiibnya saja. Cukup dengan agama Islam. Sebab, orang tidak akan masuk Islam kecuali karena sudah sampai dakwah kepadanya. Dengan demikian, engkau tahu,bahwa yang menganggap Islam sebagai syarat wajib dan sah wudhu secara bersamaan, adalah kalangan Asy-Syafi’iyah dan Hanabilah.
Madzhab Asy-Syafi’i. Mereka menambahkan tiga hal dalam syarat-syarat
sahnya wudhu yang disebutkan di atas. Pertama; Hendaknya mengetahui
tata cara wudhu. Sekiranya tidak tahu bagaimana cara berwudhu, maka
tidak sah wudhunya. Kedua; Hendaknya bisa membedakan mana yang
fardhu dan mana yang bukan dalam wudhu, kecuali jika termasuk orang
awam. Sekiranya yang wudhu adalah orang awam, maka dia tidak boleh
meyakini bahwa yang fardhu adalah sunnah, di mana jika dia menganggap
semuanya adalah fardhu, maka wudhunya sah.Ketiga; Hendaknya bemiat
pada awal wudhu dan terus begitu sampai wudhunya selesai. Karena,
jika hanya niat wudhu saat membersihkan muka saja, kemudian ketika
membasahi tangan hanya berniat untuk membersihkannya saja atau supaya
segar dengan kena air, maka wudhunya tidak sah. Mereka mengibaratkan
hal ini sebagai hukum yang menyertai niat, di mana niat harus terus
ada sampai akhir wudhu. Apabila berniat wudhu dan juga disertai niat
membersihkan, maka wudhunya tidak batal.
Madzhab Hambali. Mereka hanya menambahkan tiga hal pada syarat
sahnya wudhu. Pertama; Hendaknya menggunakan air yang boleh dipakai.
Sekiranya seseorang berwudhu dengan menggunakan air rampasan, maka
wudhunya tidak sah. Kedua; Niat wudhu. Apabila orang berwudhu tidak memakai niat, wudhunya tidak sah. Karena menurut mereka, wudhu adalah syarat sahnya shalat.
Adapun madzhab Hanafi, mereka menganggapnya sunnah, bukan rukun juga bukan syarat. Sedangkan madzhab Maliki dan Asy-Syaf i
mengatakan; bahwa niat adalah salah satu rukun wudhu. Jadi, hanya
madzhab Hambali saja yang menjadikan niat sebagai syarat wudhu. Dan
kamu akan tahu perbedaan antara syarat dan rukun nanti pada pembahasan
tentang niat. Ketiga; Mendulukan istinja’ atau istijmar atas wudhu. Menurut mereka, tidak sah wudhu tanpa hal itu. Dan penjelasannya akan datang nanti pada bab pembahasan tentang wudhu.
Fardhu-fardhu Wudhu
Fardhu secara etimologi berarti “Al Qoth’u = memotong atau
menggorok. Contoh: “Farodhtul Habl Idza Qothi’at” = Aku memotong kabel.
Adapun arti fardhu dalam istilah syar’i adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Para ahli
fikih telah mengistilahkan fardhu sama dengan rukun. Rukun sesuatu adalah fardhunya. Jadi rukun dan fardhu adalah sesuatu yang satu. Mereka membedakan antara rukun dan fardhu dengan syarat. Bahwa fardhu atau
rukun pada dasarnya merupakan hakekat dari suatu hal, sedangkan syarat
adalah kondisi di mana adanya suatu hal atau perkara bergantung padanya.
jadi syarat bukan bagian dari hakekat perkara itu sendiri. Misalnya, fardhu
shalat adalah takbir, rukuk, sujud, dll, di mana hal-hal tersebut bagian dari
shalat. Sedangkan syaratnya, misalnya telah memasuki waktu shalat. Oleh
karenanya, shalat sebelum memasuki waktunya pada dasarnya adalah
melakukan hakekat shalat tetapi tidak sah dari kacamata syariah, karena
tidak terpenuhi syaratnya.
Mengenai fardhu wudhu dalam pandangan para imam madzhab empat terdapat beberapa perbedaan. Namun fardhu wudhu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an ada empat. Pertama, membersihkan muka. Kedua,membasuh kedua tangan hingga siku. Ketiga, mengusap kepala baik seluruhnya atau sebagian. Dan keempat, mencuci kaki hingga mata kaki.
Allah Ta’ala berfirman :
“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan shalat,
maka basuhlah waj ah kalian dan kedua tangan kalian hingga siku, dan usaplah kepala serta (basuhlah) kaki kalian hingga mata kaki.” (Al-Maa’idah: 6)
Jumlah empat fardhu atau rukun ini disepakati oleh empat imam madzhab. Namun mereka berbeda dalam cara mengusap kepala.
Sebagian menyatakan mengusap kepala secara keseluruhan sebagian lain
menyatakan cukup membasuh sebagian saja dari kepala. Hal ini akan kita
bahas lebih lanjut. Namun demikian sebagian dari imam madzhab ada yang
menambahkan lebih dari empat fardhu tersebut. Mari kita ulas masing masing pendapat madzhab, sehingga tidak terjadi masalah yang tumpang tindih. Kita juga akan menunjukkan hal apa saja yang mereka sepakati.
Madzhab Hanafi mengatakan; Sesungguhnya fardhu wudhu terbatas pada empat hal ini saja. Di mana kalau seorang mukallaf berwudhu tanpa menambahi lebih dari yang empat ini, maka dia terhitung sudah wudhu.
Dia sah shalat dengan wudhu tersebut. Juga sah melakukan amalan lain
yang mengharuskan berwudhu, seperti menyentuh mushaf. Dan, engkau
akan tahu hukum orang yang meninggalkan sunnah dalam pembahasan
tentang sunnah-sunnah wudhu.
Demikian adalah penjelasan tentang empat fardhu wudhu menurut
madzhab Hanafi:
Pertama;Membasuh muka. Ini terkait beberapa perkara: satu,batasan
luasnya. Dua, apa yang wajib dibasuh dari jenggot, kumis, dan alis. Tiga,
membasuh dua mata, luar dalam. Empat,lubang hidung.
Untuk batas muka yang wajib dibasuh, bagi yang tidak punya jenggot maka batasnya adalah dari ujung rambut bagian depan kepala sampai ujung
dagu. Untuk orang botak dibasuh sampai sedikit di atas dahi. Begitu pula
dengan orang yang rambutnya tumbuh hingga dahi bahkan mendekati
alis, hukumnya sama seperti orang botak. Itu batasan wajah dari atas ke
bawah atau sebaliknya. Adapun batas lebarnya adalah dari telinga yang
satu ke telinga lainnya. Sebagian mereka menganggap batasnya adalah
bagian bawah telinga.
Adapun rambut yang tumbuh di wajah, maka yang terpenting adalah
jenggot dan kumis. Untuk jenggot, maka yang wajib dibasuh adalah yang
terdapat pada kulit wajah, dari yang paling atas hingga ujung kulit dagu.
Sedangkan yang selebihnya, tidak wajib dibasuh. Jadi, orang-orang yang
memanjangkan jenggotnya, mereka tidak wajib membasuh jenggotnya
selain yang terdapat pada kulit mukanya saja. Selebihnya, tidak wajib.
Adapun kumis, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Ada
yang mengatakan; jika kumisnya tebal, di mana air tidak bisa sampai ke
kulit, maka wudhunya batal. Dan ada yang mengatakan; tidak batal, karena
yang wajib adalah membasuh yang tampak saja, sama seperti jenggot.
Untuk rambut alis, hukumnya adalah, apabila alisnya tipis, di mana
airnya bisa sampai ke kulit, maka wajib digerakkan saja Sedangkan jika
lebat, maka ia tidak wajib disela-selai.
Untuk hidung, bagian luarnya wajib dibasuh semuanya, karena ia termasuk bagian dari wajah. Jika ada yang ditinggalkan, meski hanya sebagian kecil, wudhunya rusak. Termasuk bawahnya, di mana ada bagian yang memisahkan antara dua lubang hidung. Adapun membasuh bagian
dalamnya, ia tidak termasuk fardhu menurut madzhab Hanafi.
Demikian. Selanjutnya, jika seseorang telah berwudhu, kemudian dia
memotong jenggotnya atau rambutnya, maka wudhunya tidak batal.
Kedua; Di antara fardhu wudhu adalah membasuh kedua tangan
sampai siku. Siku, adalah tulang pemisah yang terletak di ujung lengan. Dan
terkait hal ini, ada beberapa pembahasan. Satu, jika seseorang mempunyai
jari lebih dari lima, maka ia wajib dibasuh. Adapun apabila punya tangan
tambahan, sekiranya sejajar dengan tangannya yang asli, maka wajib
dibasuh. Tetapi jika lebih panjang, maka yang wajib dibasuh cukup sebatas
yang sejajar panjang tangan yang asli saja. Adapun selebihnya tidak wajib
dibasuh, meski sebaiknya tetap dibasuh. Dua, jika di tangannya atau
kukunya ada tanah atau tepung yang menempel, maka wajib dihilangkan,
agar airnya sampai ke kulit. Kalau tidak, wudhunya batal. Begitu pula
jika panjang kukunya melebihi kulit yang ada di bawahnya, maka kuku
yang panjang tersebut juga wajib dibasuh. jika tidak, wudhunya batal.
Adapun kotoran yang terdapat di bawah kuku, menurut yang difatwakan
dalam madzhab ini, adalah tidak mengapa, karena menghindari kesulitan
dan kesusahan. Namun, sebagian ulama madzhab Hanafi ada yang
mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku tetap harus dibersihkan. Jika
tidak dilakukan, maka batal wudhunya.
Untuk bekas kutek atau tinta yang menempel pada kuku, tidak mengapa. Adapun jika inti kuteknya yang menempel pada kuku, maka
harus dihilangkan, karena menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya, apabila seseorang tangannya terpotong atau dipotong, dia wajib membasuh bagian yang masih ada. Tetapi jika bagian tangan yang wajib dibasuh terpotong semuanya, maka kewajaiban membasuh menjadi gugur.
Tiga, rnembasuh dua kaki dari sampai ke mata kaki, di mana wajib
membasuhnya hingga sedikit di atas mata kaki. Selain itu, bagian bawah
telapak kaki juga wajib dibasuh. Apabila kakinya terpotong atau dipotong,
sebagian atau seluruhnya, maka hukumnya sama dengan tangan yang
ter/dipotong di atas. ]ika kakinya atau lengannya kena minyak, lalu dia
berwudhu, dan tiba-tiba airnya mati atau habis, di mana air belum sampai
pada kulit kaki atau lengannya dikarenakan tertutup lemak, maka itu tidak
mengapa.
Sekiranya ada luka pada kakinya yang ditutupi perban atau semacamnya, di mana ia akan bertambah sakit jika air sampai padanya, maka ia tidak wajib dibasuh. Tetapi jika tidak berbahaya bagi lukanya, maka perbannya wajib dibuka agar terkena air. Selanjutnya jika terdapat sejumlah luka pada kakinya, di mana akan berakibat buruk jika terkena air, maka cukup diusap saja. Namun jika itu masih berbahaya, maka tidak wajib diusap dan dibasuh. Yang wajib dibasuh hanya yang tidak membawa madharat saja.
Keempat, di antara fardhu wudhu adalah mengusap seperempat kepala. Dan, menurut mereka ukuran sePerempat kepala adalah satu telapak tangan. ]adi, yang wajib adalah mengusap kepala minimal sebatas telapak tangan semuanya. Sekiranya telapak tangannya terkena air, lalu ia mengusapkannya ke atas kepalanya, di bagian belakang kepalanya, atau bagian depannya, atau bagian mana pun, maka itu sudah cukup.
Dan disyaratkan minimal harus menggunakan tiga jari agar airnya bisa
mengenai seperempat kepala sebelum kering. Sebab, kalau hanya dengan
dua jari saja, bisa jadi ia kering terlebih dulu sebelum digerakkan untuk
menyapu seperempat kepala. Dengan demikiary ukuran yang harus diusap
pun tidak terpenuhi. Jika dia menyapu kepala dengan semua ujung jarinya,
tetapi aimya masih menetes, di mana ia bisa menyapu ukuran minimal yang
dituntut, maka sah hukumnya. jika tidak, maka tidak sah. Dengan catatan,
mengusapnya tidak dengan air baru. Sekiranya tangannya masih basah,
itu cukup. Adapun jika mengambil basahan air dari bagian tubuh yang
atas, tidak cukup. Misal, sekiranya dia membasuh lengannya, di mananya
tangannya kering, lalu dia mengambil basahan air dari atas lengannya,
maka itu tidak cukup.
Barangsiapa yang rambutnya panjang sampai melewati dahinya atau
lehernya, lalu dia hanya mengusapnya, maka ini tidak cukup. Sebab itu
tidak mencapai seperempat kepala. Kalau orang itu botak, maka perkaranya
jelas. Sedangkan kalau rambut yang tumbuh hanya sedikit, maka rambut
di kepala tersebut diusap. Adapun jika rambut pada kepalanya tumbuh sebagian dan sebagiannya lagi botak, maka dia boleh memilih mengusap
bagian yang dia suka. Sekiranya dia mengusap rambutnya, lalu dia mencukur rambut tersebut, maka wudhunya tidakbatal. Jika dia mengusap
dengan salju, itu boleh. Kalau dia membasuh kepala sekalian dengan
mukanya, itu sudah mencukupi dari mengusap kepala, tetapi ini makruh.
Tidak boleh mengusap sorban dan semacamnya kecuali untuk orang yang
ada udzur. Begitu pula dengan perempuan, dia tidak boleh mengusap
sapu tangan atau kerudung atau semacamnya yang menutupi kepalanya,
kecuali kalau tipis yang mana air bisa tembus sampai ke kepala. Kemudian,
jika rambutnya disemir, maka harus diusap juga. Kalau airnya menjadi
berwarna semir rambut dan keluar dari hukum asal air seperti bahasan
yang lalu, maka wudhunya tidak sah. Jika tidak, hukumnya boleh.
Demikianlah fardhu wudhu menurut madzhab Hanafi. Selain yang disebutkan, maka hukumnya sunnah. Dan, penjelasannya akan dibahas
nanti.
Madzhab Maliki mengatakan; Fardhu wudhu ada tujuh:
Fardhu pertama: Niat. Berkaitan dengan ini, ada beberapa pembahasan.
1- Definisi dan tata caranya. 2- Waktu dan tempat. 3- Syarat-syaratnya. Dan,
4- Hal-hal yang membatalkan.
Untuk definisi dan tata caranya, maka ia adalah tujuan perbuatan dan keinginan untuk melakukannya. Jadi, barangsiapa yang bermaksud
hendak melakukan suatu perbuatan, maka dia dikatakan; dia telah meniatkan perbuatan itu. Adapun tata cara dalam wudhu, yaitu seseorang
meniatkan untuk menahan diri tidak berhadats kecil, atau bertujuan hendak
melakukan kewajiban wudhu, atau bermaksud menghilangkan hadats.
Secara lahir, tempat niat adalah di dalam hati. Maka, kapan pun seseorang
berwudhu dengan tata cara tersebut, sungguh dia telah berniat. Tidak ada
syarat harus dilafalkan dengan lisary sebagaimana niat juga tidak perlu
dihadirkan hingga akhir wudhu. Sekiranya dia lupa menghadirkan niat
pada saat sedang wudhu, tidak membatalkan. Selanjutnya, waktu niat adalah pada saat mulai wudhu. Apabila sudah membasuh sebagiananggota wudhu sebelum niat, maka wudhunya batal. Tetapi kalau selisih waktunya hanya sebentar, sesuai kebiasaan yang berlaku, masih dimaafkan. Sekiranya seseorang duduk untuk wudhu dan sudah berniat, kemudian datang pembantunya dengan membawakan kendi, lalu si pembantu mengucurkan air ke dua tangannya, di mana dia tidak berniat lagi, maka wudhunya sah. Sebab, jarak antara wudhu dan niatnya tidak terlalu lama. Dan, engkau sudah tahu, bahwa tempat niat adalah hati.
Adapun syaratnya ada tiga, yaitu: Islam, Tamyiz, dan jazm (niat yang
kuat). Jika ada seorang non-muslim berniat melakukan suatu ibadah, maka
niatnya tidak sah. Begitu pula dengan anak kecil yang belum mumayyiz
dan belum mengerti makna Islam. Yang juga seperti ini, adalah orang
gila. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz, maka niatnya sah. Tetapi
jika seseorang ragu-ragu dalam berniat, misalnya dia mengatakan; aku
niat wudhu jika aku telah berhadats; maka itu tidak sah. Karena, niat itu
harus betul-betul yakin. Kemudian, jika seseorang membatalkan niatnya di
tengah-tengah wudhu, maka wudhunya pun batal. Namun, jika niat untuk
membatalkan itu setelah selesai wudhu, maka tidak ada pengaruhnya.
Wudhu tetap sah. Karena, wudhu sudah sempurna. Setelah wudhu selesai,
tidak ada yang membatalkannya selain hal-hal yang membatalkan wudhu,
yang akan datang penjelasannya.
Fardhu kedua: Di antara fardhu wudhu, adalah membasuh muka.
Dari batas muka panjang dan lebarnya, adalah seperti yang disebutkan
madzhab Hanafi. Hanya saja madzhab Maliki mengatakan; Putih-putih
yang terdapat di atas dua daun telinga yang bersambung dengan kepala
dari sebelah atas, tidak wajib dibasuh, melainkan cukup diusap saja. Sebab,
ia termasuk bagian dari kepala, bukan wajah. Begitu pula dengan rambut
yang tumbuh di antara leher dan telinga, tidak perlu dibasuh, karena ia
bagian dari kepala, bukan wajah. Namun, madzhab Hanafi mengatakan
ia termasuk bagian dari wajah, di mana wajib membasuhnya.
Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang wajib
bagi mereka dalam hal ini, sama dengan yang wajib dalam madzhab
Hanafi, dalam hal membersihkan kotoran-kotoran kuku, dan kotoran yang
terdapat pada kuku yang panjang yang menutupi ujung kuku. Mereka
mengatakan; Sesungguhnya kotoran kuku itu dimaafkan, kecuali yang
tampak menjijikkan dan banyak.
Fardhu keempat: Mengusap seluruh kepala. Batas kepala dimulai dari
rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut belakang yang tumbuh di leher. Termasuk di dalamnya adalah rambut yang tumbuh
di antara telinga dan kepala, serta kulit di atas daun telinga, begitu pula
dengan kulit yang berada di atas telinga yang langsung bersambung dengan kepala. Apabila rambutnya panjang, wajib dibasuh. |ika rambutnya ada yang digelung, maka wajib diurai, dengan syarat dikepang dengan dua
tiga ikatan. Adapun jika gelungan/kepangnya terdiri dari dua ikatan atau
lebih sedikit, kalau gelungannya kuat, maka wajib diurai. Tetapi kalau
gelungannya ringan, maka tidak apa-apa. Demikian juga halnya jika
gelungan itu tanpa ikatan, baik itu digelung dengan kencang ataupun tidak.
Jadi, syarat mengurai rambut itu ketika mengusapnya ialah jika digelung
dengan beberapa ikatan. Sebagaimana yang dilakukan sebagian penduduk
negeri. Adapun apa yang dikenal di rakyat Mesir, di mana mereka mengikat
semua rambutnya tanpa gelungan, maka itu tidak apa-apa. Begitu pula
jika digelung tanpa ikatan. Engkau telah tahu, bahwa menurut madzhab
Hanafi, mengusap kepala cukup seperempatnya saja secara mutlak. Dan,
akan datang nanti penjelasan menurut madzhab Asy-Syaf i, di mana di
dalamnya ada keluwesan yang lebih banyak.
Fardhu kelima: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Sebelumnya
engkau telah mengetahui apa yang disebutkan dalam madzhab Hanafi,
bahwa mata kaki yaitu dua tulang yang menonjol di bagian bawah kaki,
di atas telapak kaki. Kaki ini wajib dibasuh bagian atas dan bawahnya.
Sekiranya bagian kaki yang wajib dibasuh ini putus semuanya, maka gugur
kewajiban membasuhnya. Sama seperti dalam madzhab Hanafi.
Fardhu keenam: Berurutan, dan biasa disebut dengan segera. Definisi
berurutan (al-muwalah), yaitu hendaknya orang yang berwudhu bersegera
membasuh anggota wudhu berikutnya sebelum anggota wudhu
sebelumnya kering. Madzhab Maliki mengatakan bahwa bersegera itu
harus dilakukan untuk seluruh anggota wudhu, baik yang dibasuh maupun
yang diusap, seperti kepala. jadi, setelah mengusap kepala, hendaknya
segera membasuh kaki. Di sini, keringnya kepala, jaraknya disamakan
dengan jarak keringnya anggota wudhu yang dibasuh. Kemudian dalam
madzhab Maliki, ada dua syarat fardhunya bersegera. Syarat pertama:
Hendaknya orang yang berwudhu itu ingat. Jadi, kalau lupa, misal dia
membasuh tangan dulu baru muka, maka wudhunya sah. Namun jika dia
teringat, dia harus mengulangi niatnya ketika menyempurnakan wudhu. sebab, niatnya telah batal saat dia lupa. syarat kedua: Karena tidak mampu
melakukan dengan muwalah (bersegera), tanpa menyepelekan. Misalnya,
dia berwudhu dengan menggunakan air secukupnya dalam satu wadah.
Dia yakin bahwa air itu cukup untuk wudhu. Tetapi temyata airnya kurang.
Dia sudah membasuh sebagian anggota wudhunya, seperti wajah dan dua
tangan, namun dia masih membutuhkan air lagi untuk menyempurnakan
wudhunya. Lalu, dia pun menunggu datangnya air hingga kering anggota
wudhu yang telah dibasuh. Dalam kondisi demikian muwalah menjadi
gugur. Dan, saat air datang, dia tinggal melanjutkankan wudhunya.
Meskipun jarak waktunya lama. Adapun jika dia sudah menyepelekan dari awal, di mana sebetulnya dia sudah ragu bahwa airnya tidak akan cukup dipakai wudhu, maka jika lewat waktu yang lama sehingga kering anggota wudhunya yang sudah dibasutu maka batal wudhunya. Tetapi jika waktunya hanya sebentar, tidak batal.
Fardhu ketujuh: Menggosok anggota wudhu, yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu. ini hukumnya fardhu.
Sama seperti menyela-nyelai rambut dan jari-jari tangan.
Dengan demikian, engkau telah mengetahui bahwa fardhu wudhu menurut madzhab Maliki ada tujuh: niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh dua kaki hingga mata kaki, bersegera, dan menggosok. Kenapa menggosok dianggap fardhu, padahal ia termasuk dalam membasuh menurut mereka, karena ia merupakan mubalaghah (hiperbola) dalam penekanannya. Dan, makna
bahwa ia termasuk dalam hakekat membasuh, karena menurut madzhab
Maliki, ia tidak sekadar mengguyurkan air saja ke anggota wudhu, melainkan harus disertai dengan menggosok.
Madzhab Asy-Syafi’i mengatakan; Fardhu wudhu ada enam, yaitu:
Fardhu pertama: Niat. Definisinya, syarat-syaratnya, dan pembahasan pembahasan lainnya tidak berbeda dengan apa yarlg telah disebutkan
dalam madzhab Maliki sebelum ini, kecuali dalam dua hal. Yang pertama,
bahwasanya Malikiyah mengatakan tidak disyaratkannya mengaitkan
niat dengan perbuatan-perbuatan wudhu. Menurut mereka (Malikiyah),
dimaafkan berniat terlebih dulu sebelum wudhu dalam waktu yang tidak
begitu lama menurut kebiasaan yang berlaku. Adapun menurut Asy-
Syah’iyah, niat itu harus bareng dengan permulaan wudhu. Sekiranya anggota wudhu yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, maka niat itu
dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Jika saat membasuh wajah
tidak disertai dengan niat maka wudhunya batal. Sekiranya dia sudah bemiat
ketika pertama kali membasuh muka, kemudian setelah itu lupa, maka itu
sudah cukup. Sebab, niat ini tidak harus selalu dilakukan selama membasuh
muka. Lalu, apabila dia berniat ketika membasuh dua tangan, atau saat
memasukkan air ke dalam hidung atau pada waktu mengeluarkannya, maka
niatnya tidak sah. Karena itu adalah bagian dari wajah. Jika dia berniat pada
saat membasuh bagian luar dari dua bibirnya ketika berkumur-kumur, maka
niatnya sah. Karena itu adalah bagian dari wajah.
Kemudian jika dia bermaksud membasuhnya dikarenakan itu bagian
dari wajah, maka dia tidak harus mengulangnya. Adapun kalau dia
bermaksud melakukan sunnah saja, atau tidak bermaksud apa-apa, maka
dia mesti membasuh ulang. Lalu, apabila pada wajahnya terdapat luka
yang tidak bisa dibasuh, maka niat berpindah untuk membasuh lengan.
Yang keilua, kalangan Asy-Syafi’iyah mengatakan; Sesungguhnya
niat menghilangkan hadats dalam wudhu adalah tidak sah, sebagaimana
disebutkan kalangan Malikiyah. Tetapi ini hanya sah bagi orang yang sehat.
Adapun orang yang puny a udzur , seperti penderita penyakit enuresis (tidak
bisa menahan kencing), dia harus berniat untuk dibolehkan shalat atau
menyentuh mushaf, dan sebagainya, di mana untuk melakukannya wajib
berwudhu dulu. Atau, bisa juga dia berniat menunaikan kewajiban wudhu.
Sebab, hadatsnya tidak hilang dengan wudhu. Sekiranya dia berniat
menghilangkan hadats dengan wudhunya, hadatsnya tetap tidak hilang.
Sesungguhnya, dia disyariatkan berwudhu agar boleh melaksanakan shalat
atau melakukan suatu amalan yang harus memakai wudhu.
Fardhu kedua: Membasuh muka. Adapun batasan wajah, panjang dan
lebarnya yaitu sama seperti yang terdapat pada madzhab Hanafi. Hanya
saja madzhab Asy-Syafi’i mengatakan; Sesungguhnya apa yang di bawah
dagu, wajib dibasuh. Ini termasuk pendapat madzhab Asy-Syafi’i yang
berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya. Namun, mereka sepakat
dengan madzhab Maliki dan Hambali bahwa jenggot yang panjang
mengikuti wajah (termasuk bagian dari wajah), di mana wajib dibasuh
semuanya. Hal ini berbeda dengan madzhab Hanafi, sebagaimana yang
telah engkau ketahui.
Madzhab Asy-Syafi’i sepakat dengan madzhab Hanafi, bahwa rambut yang ada di antara leher dan telinga, serta bagian yang terdapat di atas daun
telinga, adalah bagian dari wajah. Untuk itu, ia wajib dibasuh menurut
mereka. Berbeda dengan madzhab Maliki dan Hambali. Adapun menyelai nyelai jenggot, madzhab Asy-Syafi’i sama dengan madzhab yang lain, yakni
jika jenggotnya tipis, maka wajib disela-selai sampai aimya mengenai kulit.
Sedangkan jika jenggotnya lebat, maka yang wajib dibasuh adalah yang
tampak saja, namun sunnah jika disela-selai. Meski demikian, madzhab
Maliki mengatakan; Sesungguhnya jenggot yang lebat, sekalipun tidak
wajib disela-selai, tetapi ia wajib digerak-gerakkan dengan tangan, agar
aimya masuk ke tengah-tengah jenggo! meskipun tidak sampai kena kulit.
Adapun menyela-nyelai, ia tidak wajib. Jadi, para imam sepakat bahwa menyela-nyelai jenggot yang tipis di mana air bisa sampai ke kulit adalah wajib. Bukan dengan maksud agar air sampai ke kulit, melainkan untuk membasuh jenggot sebisa mungkin dengan mudah. Selain itu, salah.
Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai siku. Madzhab Asy-Syafi’i dan Hanafi sepakat dalam hal ini, namunperlu penjelasan lebih rinci.
Hanya saja mereka (Asy-Syafi’iyah) mengatakan; Sesungguhnya kotoran kotoran yang terdapat di bawah kuku, jika ia menghalangi sampainya air
ke kulit, maka ia wajib dihilangkan. Tetapi, ia dimaafkan bagi para pekerja
yang bersentuhan dengan tanah dan yang semacamnya, dengan catatan
kotorannya tidak banyak, sehingga menutupi ujung jari.
Fardhu keempat: Mengusap sebagian kepala meskipun sedikit. Dan,
tidak disyaratkan mengusap dengan tangan. Sekiranya orang tersebut
menyiramkan air ke sebagian dari kepalanya, itu sudah cukup. Jika ada
rambut pada kepalanya,lalu dia usap sebagiannya, itu sudah sah. Adapun
jika rambutnya panjang menjulur sampai ke tengkuk atau lebih, lalu dia
mengusap rambutnya yang di tengkuk, itu tidak cukup, sekalipun dia
menariknya sampai ke atas kepala. Menurut mereka, mengusap kepala
itu, harus mengenai rambut yang menempel di atas kepala. Mereka juga
mengatakan, apabila kepala dibasuh dan tidak mengusapnya, maka itu
juga boleh. Tetapi itu menyalahi yang lebih utama, namun tidak makruh.
Sebagaimana madzhab yang lain juga mengatakan demikian.
Fardhu kelima: Membasuh dua kaki dari mata kaki. Dalam hal ini,
madzhab Asy-Syafi’i sepakat dengan madzhab Hanafi dan selain mereka.
Fardhu keenam: Urut atau tertib di antara empat anggota wudhu yang
disebutkan dalam Al-Qur’anul karim. Harus dimulai dengan membasuh
wajah, kemudian dua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, terus
membasuh dua kaki sampai mata kaki. Apabila mendahulukan atau
mengakhirkan dari urutan ini, maka wudhunya batal. Madzhab Hambali dan
Maliki sepakat dengan Asy-Syafi’iyah dalam hal ini. Sedangkan Hanafiyah
mengatakan, urutan dalam wudhu adalah sunnah, bukan fardhu.
Dengan demikian, engkau tahu, bahwa fardhu wudhu menurut
madzhab Asy-Syafi’i ada enam, yaitu : niat, membasuh muka, membasuh
dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki
sampai mata kaki, dan urut.
Madzhab Hambali mengatakan; Fardhu wudhu ada enam.
Pertama: Membasuh muka. Untuk batas panjang dan lebar muka, mereka
sepakat dengan madzhab Maliki. Mereka mengatakan, sesungguhnya bagian antara leher dan belakang telinga, serta bagian yang terletak di atas
daun telinga, adalah termasuk bagian dari kepala, bukan muka. jadi yang
wajib adalah mengusap keduanya, bukan membasuh keduanya. Hanya saja,
mereka berselisih pendapat dengan para imam madzhab yang lain dalam
hal memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Mereka mengatakan,
keduanya termasuk bagian dari muka, jadi wajib dibasuh dengan kumur kumur dan memasukkan air ke dalam hidung.
Begitu pula, mereka berbeda dengan para imam yang lain dalam
masalah niat. Menurut mereka, ia adalah syarat sahnya wudhu. Jika
seseorang tidak berniat, maka tidak sah wudhunya. Sekalipun niat bukan
fardhu yang masuk dalam hakekat wudhu. Dan, engkau telah mengetahui
bahwa madzhab Maliki dan Asy-Syaf i mengatakan bahwa niat adalah
fardhu. Sementara madzhab Hanafi mengatakan, niat adalah sunnah.
Kedua: Membasuh dua tangan sampai siku. Jadi, wajib membasuh
tangan dari ujung jari sampai ujung tulang siku, sebagaimana disebutkan
madzhab Hanafi dan selain mereka. juga wajib membasuh ujung jari dan
kotoran yang terdapat di bawah kuku yang panjang. Adapun jika kotoran
kukunya sedikit, dimaafkan. Ketiga: Mengusap semua kepala, termasuk dua telinga. Jadi, wajib mengusapnya bersama kepala. Madzhab Hambali sepakat dengan madzhab Maliki dalam hal wajibnya mengusap seluruh kepala, dari ujung tumbuhnya rambut depan sampai ke tengkuk. Sekiranya rambutnya panjang melebihi leher belakang, maka yang wajib diusap hanya yang sejajar dengan kepala saja. Ini sedikit berbeda dengan Malikiyah yang mengatakan seluruh rambut wajib diusap.
Hanabilah juga berbeda dengan madzhab-madzhab lain dalam hal telinga termasuk bagian dari kepala, di mana menurut selain Hanabilah, membasuh kepala sudah mencukupi dari mengusapnya. Dengan syarat, tangan tetap diusapkan ke kepala. Dan, ini makruh, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Keempat: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Hal ini sama dengan madzhab-m adzhab yang lain. Kelima: Urut. Wajib membasuh muka sebelum tangan, membasuh tangan sebelum mengusap kepala, dan mengusap kepala sebelum membasuh kaki. Apabila urutan ini dilanggar, maka batal wudhunya. Mereka sepakat dengan Asy-Syafi’iyah dalam hal ini. Adapun Hanafiyah dan Malikiyah, mereka menganggap urut ini sebagai sunnah. Jika ada orang mendulukan membasuh tangan sebelum muka, atau membasuh kaki duluan sebelum tangan maka wudhunya sah menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah tetapi makruh.
Keenam: Al-muwalah (bersegera). Sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya dalam madzhab Maliki, muwalah adalah segera. Maksudnya,
membasuh anggota wudhu sebelum anggota wudhu yang sebelumnya
kering. Adapun menurut madzhab Asy-Syafi’i dan Hanafi, bersegera
membasuh anggota wudhu berikutnya ini adalah sunnah, bukan fardhu.
Itulah, makruh hukumnya membasuh anggota wudhu setelah air pada
anggota wudhu sebelumnya kering.
Secara umum, fardhu wudhu menurut madzhab Hambali, yaitu:
membasuh muka; termasuk bagian dalam mulut dan hidung, membasuh
dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala; termasuk dua telinga,
membasuh dua kaki, urut, dan segera.
Ringkasan
Para imam dari empat madzhab sama-sama sepakat mengenai empat fardhu sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an: membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala seluruhnya atau
sebagian, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Madzhab Hanafi
tidak menambahkan sesuatu apa pun selain itu, berbeda dengan tiga imam
yang lain.
Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai batas membasuh wajah. Madzhab Asy-Syafi’i, madzhab Maliki, dan madzhab Hambali menyatakan batas membasuhwajah dimulai dari batas normal tumbuhnya rambut hingga berujung di akhir dagu bagi yang tidak berjenggot.
Bagi yang berjenggot membasuhnya hingga ujung rambut jenggotnya meskipun panjang. Hanya saja menurut Asy-Syafi’i bagian bawah dagu
masih merupakan bagian wajah yang harus dibasuh. Sedangkan Hanafi
menyatakan bahwa batas wajah adalah dari batas normal tumbuhnya rambut hingga akhir dagu. Bagi yang memiliki jenggot memanjang melebih batas ujung dagu tidak harus dibasuh. Pandangan ini sejalan dengan madzhab Maliki dan Hambali, bahwa apa yang di bawah dagu tidak harus dibasuh.
Madzhab Asy-Syafi’i dan Hanafi sepakat bahwa pentil telinga merupakan bagian dari wajah yang harus dibasuh. Berbeda dengan Maliki dan Hambali yang menyatakan bahwa pentil telinga merupakan bagian dari kepala, sehingga cukup diusap saja, tidak perlu dibasuh.
Para imam sepakat bahwa jika jenggot yang tumbuh tidak panjang melainkan tipis pendek dan masih tampak bagian kulit yang ditumbuhinya,
maka harus disela-selai sehingga air bisa mengenai kulit. Akan tetapi jika jenggotnya lebat cukup dibasuh bagian luarnya saja dan tidak harus diselai selai, hanya disunnahkan saja. Akan tetapi madzhab Maliki menyatakan
bahwa rambut jenggot yang tebal meskipun tidak harus disela-selai, tetapi
tetap harus dibasuh dan digerak-gerakkan dengan tangan, dalam rangka
untuk mengenakan air disela-sela rambut meskipun tidak sampai pada
kulit. Tiga imam madzhab sepakat bahwa telinga bukan bagian dari wajah,
berbeda dengan Hambali yang menyatakan bahwa kedua teliha merupakan
bagian dari wajah yang harus dibasuh dengan air.
Madzhab Hambali dan Maliki sepakat untuk mengusap kepala secara keseluruhan sementara madzhab Hanafi dan Asy-Syafi’i berpendapat yang
harus diusap cukup sebagian kepala, kalaupun seluruhnya itu hukumnya
sunnah. Tetapi Asy-Syafi’i menyatakan bahwa yang wajib diusap hanya
sebagian dari kepala walaupun sedikit. Lain halnya dengan Hanafi yang
mengatakan bahwa batas minimal yang wajib diusap adalah seperempat
kepala, sebab itu merupakan ukuran telapak tangan.
Madzhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa tertib anggota wudhu bukan merupakan fardhu, melainkan sunnah. Jadi sah misalnya membasuh tangan sebelum membasuh muka atau yang lain. Berbeda madzhab Asy-Syafi’i dan Hambali yang berpendapat bahwa tertib wudhu merupakan fardhu.
Madzhab Maliki dan Asy-Syaf i sepakat bahwa niat adalah fardhu, tetapi mereka berbeda dalam hal waktu berniat. Madzhab Maliki menyatakan bahwa niat dilakukan sesaat sebelum mengerjakan wudhu, yaitu sesaat menurut ukuran kebiasaan umum. Sementara menurut Asy-Syaf i niat harus dilakukan ketika memulai membasuh muka, atau fardhu yang pertama jika seseorang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk membasuh wajah. Madzhab Hambali dan Hanafi juga berbeda pendapat.
Menurut madzhab Hambali, niat merupakan syarat, bukan fardhu. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, niat adalah sunnah.
Madzhab Asy-Syafi’i dan Hanafi sepakat bahwa menyegerakan dalam membasuh anggota-anggota wudhu adalah sunnah, bukan fardhu. Maksudnya, yaitu membasuh anggota wudhu sebelum anggota yang sebelumnya mengering. Sementara madzhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa menyegerakan seperti itu adalah fardhu.
Bersambung ke Bab :
SUNNAH-SUNNAH WUDHU